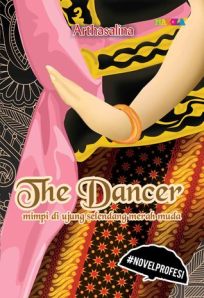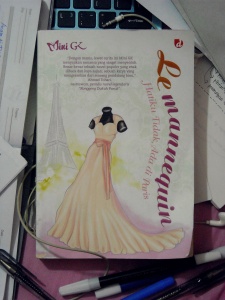Judul: The Dancer (Mimpi di Ujung Selendang Merah Muda)
Penulis: Arthasalina
Penerbit: Mazola
Rilis: September 2014
ISBN : 139786022960225
Jumlah halaman: 235
Genre: Fiksi
Banyak yang bilang keadaan hatiku bisa dilihat dari bagaimana aku menari. Katanya lebih jujur daripada mendengar jawaban dari mulut. Mungkin aku memang ditakdirkan untuk terjun ke sini, menari bersama hidup. Bukan hidup bersama tarian–Ajeng (halaman 155-156)
Menjadi penari tradisonal di zaman yang sudah modern seperti sekarang rupanya tidak mudah. Terlebih bila telah terlanjur meraih gelar sarjana kedokteran kemudian dihadapkan dengan dua pilihan. Tetap menjadi penari sesuai impian atau melanjutkan koas untuk menjadi dokter, seperti harapan ayahnya. Hal rumit itulah yang diadapi oleh Ajeng. Sejak ibunya meninggal karena kanker, ia memutuskan mengikuti kata hatinya untuk menjadi penari. Yang berarti ia juga menetang ayahnya. Baginya menjadi penari seperti menghadirkan kembali sosok ibunya yang juga sama-sama penari. Tidak mudah menjalani pilihan itu. Di samping ayahnya yang menolak keras pilihan itu karena berambisi anak-anaknya bisa menjadi dokter.
Menjadi penari adalah profesi yang kurang bergengsi bagi masyarakat pada umumnya. Terlebih profesi tersebut masih dipandang sebelah mata. Namun Arthasalina, penulis novel ini, seperti menceritakan pada kita bahwa tidak sekedar menghibur saja tujuan seorang penari, melainkan ada misi melestarian budaya dalam proses itu.
Meski halangan dan rintangan terjadi, Ajeng bertekad kuat berada di jalan itu. Ia juga mengikuti berbagai lomba dan pementasan, bahkan sempat menjadi penari sintren, seenis tarian tradisional yang melibatkan roh. Di tengah-tengah kesibukannya meniti karier di bidang menari, ia pun berusaha memajukan sanggar tari milik ibunya yang sudah lama tidur. Belum lagi ketika ia dihadapkan dengan rahasia besar yang akhirnya terkuak dan mengharuskan ia harus menentukan sesuatu yang berhubungan dengan masa lalu ayahnya. Yang juga berkorelasi dengan seorang tokoh di novel tersebut yang berjasa dalam perjalanan kariernya.
Adapun Deden, adalah salah satu mahasiswa Teknik Mesin yang memutuskan mengambil cuti dan datang ke Jawa (Jogja-Solo) untuk mencari pengalaman secara praktik, di samping merasa suntuk dengan kehidupan kota. Ia adalah orang yang semula menolak hal-hal yang berhubungan dengan budaya, bahkan tidak suka dengan pertunjukan tari. Namun, perjalanannya ke Jogja-Solo membuatnya jatuh cinta dengan Jawa dan orang-orangnya. Cara pandangnya mulai berubah sejak perkenalannya dengan Ajeng dan pertemuannya secara tidak sengaja. Deden yang berasal dari tradisi yang lebih metropolitan pun mengagumi sifat santun Ajeng juga. Kehadiran Ajeng sedikit banyak mengubah sikap Deden.
“Bukan masalah orang jawa atau bukan, Mas. Sebenarnya masalah kebiasaan. Saya yakin adat mana pun juga mengajarkan hal yang sama. Mungkin kebiasan yang ada di lingkungan sekitar kita yang mengubahnya.”–Ajeng (halaman 59)
“Orang Jawa atau bukan, yang membuat kesan sopan dan punya tata krama itu perilakuknya”-Ajeng (halaman 60)
Deden nyaris tak pernah menemukan perempuan seunik Ajeng. Di sisi lain, Ajeng pun nyaman dengan kebersamaan mereka. Namun, sebelum mereka sama-sama saling tahu perasaan masing-masing, Deden keburu pindah lagi ke Bandung karena cuti kuliahnya habis. Selama setahun mereka tak bertemu bahkan tak terhubung melalui ponsel. Selama itu Ajeng yang bergelut dengan karier menarinya, sedangkan Deden sibuk dengan kelulusan dan pekerjaan barunya. Apakah kelak mereka bersama, atau Ajeng lebih memilih Andi, teman seprofesi denganya di dunia tari?
“Pria dewasa itu menentukan pilihan, sebatas memlilih ketentuan bukan karakter pria.” (halaman 56) demikian yang Deden ingat dari pertemuannya dengan Ajeng.
Novel The Dancer (Mimpi di Ujung Selendang Merah Muda) diakhiri dengan ending yang manis dan membuat saya tersenyum. Memang pembaca mungkin akan mudah menebaknya dari awal. Sisi menariknya adalah banyak pesan penting yang dapat ditemukan di dalam dialog-dialog tokohnya yang sarat dengan pengetahuan seputar local wisdom.
Novel ini menceritakan perjuangan mempertahankan pilihan dan tentang usaha yang tidak kenal lelah. Diceritakan dalam sudut padang orang pertama yang terdiri dari dua tokoh, yaitu Ajeng sebagai tokoh sentral dan Deden sebagai tokoh pendukung. Keduanya memiiki karakter yang berbeda. Ditunjukkan dengan Pov Ajeng yang menggunakan gaya bahasa “aku-kamu”, sedangkan Deden menggunakan” lo-gue”, menunjukkan perbedaan tradisi dan karakternya juga. Setting tempat ini adalah Semarang, Solo, Bandung, meskipun ada lokasi-lokasi lain, dan rata-rata tidak dideskripsikan secara lebih lengkap.
Keberhasilan novel ini terletak pada jalan ceritanya yang runut dan ide cerita yang membuat penasaran, juga pesan-pesan yang disertakan dalam dialog tokoh-tokohnya. Gaya bahasa dituturkan dengan ringan dan mudah dipahami. Dilengkapi pula beberapa footnote untuk memperkaya pengetahuan kita terhadap bahasa daerah. Terutama Jawa dan Sunda. Di samping itu, secara samar, penulis juga memperkenalkan budaya yang yang berasal dari nenek moyang sehingga tersampaikan misi penulis memperkenalkan budayanya, terutama tradisi tari. Seperti halanya cara Ajeng memperkenalkan keramahtamahan orang jawa terhadap Deden.
Cover buku ini sudah sesuai dengan tema dan judulnya, The Dancer (Mimpi di Ujung Selendang Merah Muda) meskipun sepertinya tidak akan ada masalah bila judul tersebut tidak menggunakan bahasa Inggris, mengingat novel tersebut, lebih sering menampilkan sisi kedaerahan dan ke-Indonesia-an. Di samping itu, saya pribadi barangkali agak merasa mengganjal dengan hal-hal yang kebetulannya agak dipaksakan. Seperti ketika secara tidak sengaja, Deden bertemu istri seorang teman di sebuah terminal bus, apalagi ia belum mengenal si istri temannya itu sebelumnya. Atau secara kebetulan ia bertabrakan dengan Ajeng di daerah ladang lereng gunung yang rata-rata luas dan masih “alas”. Yeah, meskipun dalam hidup ini hal-hal yang kebetulan bukan sesuatu yang mustahil, tapi alangkah baiknya dikondisikan selogis mungkin. Selain itu, sejak awal perkenalan, Deden terlalu beranggapan bahwa orang Jawa selalu indah, santun, suka gotong royong, dan wanitanya feminin. Padahal stereotype orang Jawa nggak selalu begitu. Terlebih di era sekarang. Bukankah demikian?
Penokohan Ajeng dan Deden yang berbeda karakter sudah cukup pas digambarkan sebagai tokoh utama dan bagian dari tema novel. Hanya saja konstruksi karakter sang ayah kurang begitu konsisten sebab di awal ia digambarkan sebagai sosok yang membenci dunia tari. Terlihat dari keukeuhnya ia menyuruh Ajeng melanjutkan koas dan melarangnya menari, namun ibu Ajeng sendiri adalah penari. Belum lagi masa lalunya yang menunjukkan bahwa penokohan sang ayah kurang sesuai sebagai sosok yang menentang profesi penari. Atau kalaupun iya, kurang diberi penjelasan.
Di samping itu, alur terasa agak tergesa dan oleh karenanya banyak detail yang kurang mendapat perhatian penulis dalam hal dialog dan penuturan, seperti pada halaman 30 di mana Mak Atun, mengatakan “wis tuwo” untuk menyebut nenek Ajeng, sebab dalam Jawa puya tingkatan bahasa, akan lebih tepat bila disebut dengan “sampun sepuh“. Selain itu penggambaran setting tampaknya perlu disempurnakan lagi dengan detail dan ciri khas, sebab meski sempat disebutkan nama-nama lokasi, seperti Sleman, namun belum kentara andaikata nama daerahnya diubah menjadi Kebumen atau Padang, misalnya. Lagipula (merujuk pada halaman 213) makanan jenis batagor tidak hanya ada di Bandung, Solo pun ada.
Namun tidak mengapa. Barangkali memang bukan pada deskripsi setting,dan detail masyarakat secara kebudayaan yang istimewa dari novel ini. Sesuai dengan konsep awalnya, novel ini sudah menggambarkan cerita hidup orang-orang yang bergulat dengan profesinya, yang tentunya tidak lepas dari kehidupan pribadi yang juga cukup berliku. Seperti halnya seorang penari. Sekalipun seorang penari dapat tampil total dan tersenyum tanpa beban di atas pentas, mereka juga tetap manusia biasa di balik panggung. Selebihnya tidak banyak kesalahan tata bahasa, typo, dan ejaan di sana, pun sudah lumayan penataan marginnya.
Novel ini direkomendasikan suntuk pembaca dewasa muda yang sedang mempertahankan pekerjaan sejatinya.